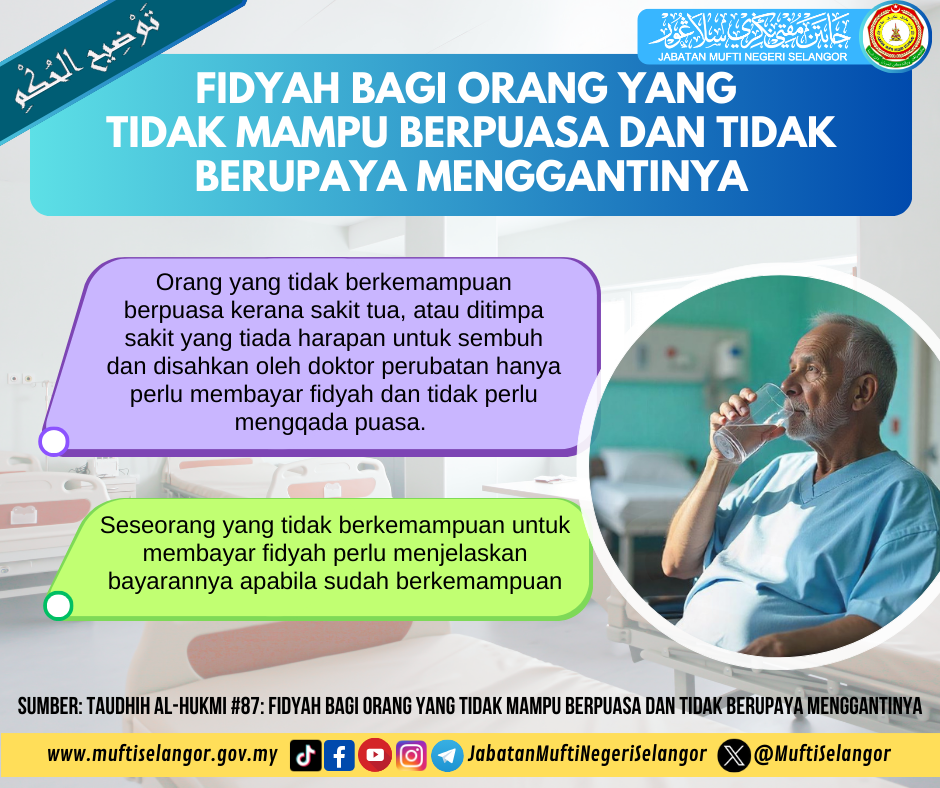Fidyah bagi Orang yang Tidak Mampu Berpuasa dan Tidak Berupaya Menggantinya
Disediakan oleh: Unit Dirasat Ilmiah
Tarikh: 8 April 2025
Pendahuluan
Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia dan diwajibkan padanya berpuasa ke atas setiap Muslim yang memenuhi syaratnya. Meskipun begitu, terdapat beberapa keadaan yang diberikan rukhṣah (keringanan) untuk tidak berpuasa dengan mengqadanya, atau membayar fidyah atau, kedua-duanya sekali, seperti sakit, haid, hamil, dan sebagainya.
Dalam perbahasan ini, perintah untuk mengqada puasa dan membayar fidyah bagi puasa yang ditinggalkan jelas dinyatakan dalam firman Allah SWT di dalam Surah al-Baqarah ayat ke-184:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ
Maksudnya: (Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu); maka sesiapa di antara kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah dia berbuka), kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin.
Bagi seseorang yang muda, tua dan sihat, jika dia meninggalkan puasa, maka dia tetap perlu menggantinya. Justeru, bagaimana pula keadaan seseorang yang tidak mampu berpuasa dan tidak berupaya menggantinya?
Golongan yang Tidak Mampu Berpuasa dan Tidak Berupaya Menggantinya
Golongan yang dinyatakan di atas boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu:
Pertama, orang sakit yang disahkan menghidap penyakit kritikal oleh doktor perubatan di mana mereka tiada harapan untuk sembuh dan tiada ubat untuk penyakitnya.
Kedua, orang tua yang tidak lagi berkemampuan untuk berpuasa disebabkan keuzurannya.
Bagi kedua-dua golongan ini, mereka tidak perlu qada puasa, sebaliknya hanya perlu membayar fidyah sahaja, iaitu bersamaan secupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hal ini sepertimana yang disebutkan dalam al-Taqrīrāt al-Sadīdah:
مَا يَلْزَمُ فِيهِ الفِدْيَةُ دُوْنَ القَضَاءِ: كَشَيْخٍ كَبِيـرٍ، وَالـمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ[1]
Maksudnya: Perkara yang hanya dikenakan fidyah tanpa perlu qada adalah sepertimana keadaan orang tua yang uzur, dan orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh.
Perkara ini dibahaskan bersandarkan kepada ayat وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Sheikh Abū Bakr Uthmān Shaṭā dalam I‘ānat al-Ṭālibīn menjelaskan makna ayat tersebut, bahawa:
أَيْ: لَا يُطِيقُونَهُ، أَوْ أَنَّ الـمُرَادَ يُطِيقُونَهُ فِـي الشَّبَابِ وَالصِّحَّةِ ثُـمَّ يَعْجِزُونَ عَنْهُ بَعْدَ الكِبَـرِ أَوِ الـمَرَضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ[2]
Maksudnya: Iaitu tidak berkemampuan berpuasa atau yang dimaksudkan adalah berkemampuan ketika usia mudanya dan ketika sihat, kemudian menjadi lemah kerana semakin berumur (uzur) atau ditimpa sakit yang tiada harapan untuk sembuh.
‘Atā’ – rahimahullah – meriwayatkan bahawa beliau mendengar Ibn Abbās RA mengatakan:
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيـنٍ)، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِـمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيـرُ، وَالـمَرْأَةُ الكَبِيـرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا[3]
Maksudnya: (Dan diwajibkan ke atas mereka untuk berpuasa, lalu mereka tidak terdaya untuk berpuasa. Maka, mereka perlu memberi makan kepada orang miskin). Kata Ibn ‘Abbas: Ayat ini tidak dinasakhkan (dimansuhkan) pada hak lelaki dan perempuan yang uzur yang mana mereka tidak mampu berpuasa, lalu mereka perlu memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.
(Riwayat al-Bukhārī)
Oleh itu, dapat difahami bahawa ibadah puasa Ramadhan pada asalnya adalah wajib ke atas semua mukalaf, namun disebabkan kekangan faktor umur yang kian meningkat dan uzur, atau kerana ditimpa sakit yang tiada harapan untuk sembuh, maka dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadanya mengikut kesepakatan para ulama. Bahkan, mereka hanya perlu melunaskan tuntutan fidyah sahaja.
Situasi Membayar Fidyah bagi Kedua-dua Kategori Ini
Bagi seseorang yang mūsir (berkemampuan), maka adalah seeloknya dia tidak menangguhkan bayaran fidyah ini agar segera terlepas dari kewajipan tersebut. Tuntutan tersebut tetap perlu dipenuhi melalui harta pusakanya walaupun setelah dia meninggal jika dia berkemampuan dan berkesempatan, tetapi tidak membayarnya ketika masih hidup.
Adapun bagi seseorang yang mu‘sir (tidak berkemampuan), maka dia dituntut untuk membayarnya apabila sudah berkemampuan di kemudian hari melainkan jika dia meninggal sebelum berkemampuan.[4] Hal ini kerana tuntutan fidyah ini merupakan hak Allah SWT yang tidak akan gugur ketika tidak berkemampuan selagi mana seseorang itu masih hidup. Imam al-Ramlī mengatakan:
بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَـى الـمَالِـيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ العَبْدُ وَقْتَ الوُجُوبِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ البَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِـخِلَافِ زَكَاةِ الفِطْرِ[5]
Maksudnya: Hak Allah SWT yang melibatkan harta, jika seseorang hamba tidak mampu untuk memenuhinya ketika diwajibkan ke atasnya, maka ia kekal dalam tanggungannya walaupun ia tidak diwajibkan sebagai ganti kepada sesuatu, tapi diwajibkan kerana perbuatannya. Dalam konteks ini, ia sememangnya berlaku disebabkan perbuatannya, iaitu tidak berpuasa, berbeza dengan zakat fitrah.
Dengan ini, maka jelas bahawa yang menjadi wajib ke atasnya adalah fidyah, bukan lagi puasa. Namun, jika dia berkemampuan untuk berpuasa di kemudian hari, contohnya seseorang yang diberikan kesembuhan dari penyakit kritikal tanpa diduga selepas berlalunya Ramadhan, maka terdapat dua pandangan fuqaha mazhab Shāfi‘ī berkenaan isu ini.
Majoriti mereka seperti al-Khaṭīb al-Sharbīnī,[6] al-Ramlī,[7] al-Haytamī[8] dan yang lain berpendapat bahawa jika dia berkemampuan untuk berpuasa di kemudian hari, maka dia tidak perlu mengqada puasa lepas walaupun kemampuan itu datang sebelum dia membayar fidyah. Akan tetapi, terdapat segelintir fuqaha mazhab Shāfi‘ī seperti Ibn Rif‘ah[9] yang berpendapat bahawa dia wajib mengqada puasa lepas jika dia berkemampuan untuk berpuasa di kemudian hari dan fidyah bukan lagi menjadi pilihannya. Namun, pandangan pertama lebih tepat kerana kewajipan puasa telah gugur daripadanya sejak dia menjadi uzur atau mula menghidap penyakit yang tiada harapan untuk sembuh.
Perkara ini dinyatakan secara ringkas dalam I‘ānat al-Ṭālibīn:
وَهَلْ الفِدْيَةُ فِـي حَقِّهِ وَاجِبَةٌ ابْتِدَاءً أَوْ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ؟ وَجْهَان. أَصَحُّهُمَا: الأَوَّلُ. فَعَلَيْهِ: لَوْ قَدِرَ عَلَى الصَّوْمِ بَعْدَ فَوَاتِهِ: لَـمْ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ – سَوَاءٌ كَانَتْ قُدْرَتُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الفِدْيَةِ، أَوْ قَبْلِهِ – لِأَنَّهُ مُـخَاطَبٌ بِالفِدْيَةِ ابْتِدَاءً[10]
Maksudnya: Adakah fidyah bagi haknya (orang ditimpa keuzuran yang tidak akan hilang) diwajibkan sejak mula atau ia adalah ganti kepada puasa? Terdapat dua pandangan, yang paling tepat adalah pandangan pertama (iaitu diwajibkan sejak mula). Oleh itu, jika dia mampu untuk berpuasa di kemudian hari, maka dia tidak wajib qada puasa yang ditinggalkan sama ada kemampuan itu datang selepas dia membayar fidyah atau sebelumnya kerana dia dituntut untuk membayar fidyah sejak mula.
Hukum-hakam Berkaitan Kedua-dua Kategori Ini
- Jika dia bernazar untuk berpuasa, maka nazarnya tidak sah.[11]
- Jika dia tetap berpuasa sambil menanggung kepayahan dan kesakitannya, maka puasanya dikira dan dia tidak dituntut untuk membayar fidyah bagi hari tersebut.[12]
- Dia hanya boleh mula membayar fidyah tersebut hanya setelah masuknya bulan Ramadhan, iaitu apabila bermulanya kewajipan berpuasa atau fidyah.[13]
- Jika dia melewatkan pembayaran fidyah tersebut hingga ke tahun-tahun berikutnya, maka tiada sebarang penambahan fidyah dikenakan atas kelewatannya.[14]
Kesimpulan
Orang yang tidak berkemampuan berpuasa kerana sakit tua, atau ditimpa sakit yang tiada harapan untuk sembuh dan disahkan oleh doktor perubatan tidak perlu mengqada puasa. Sebaliknya, dia hanya perlu menjelaskan bayaran fidyah walaupun sekiranya dia sihat dan mampu untuk berpuasa di kemudian hari. Jika dia tidak berkemampuan untuk membayar fidyah, maka kewajipan tersebut perlu dipenuhi apabila dia sudah mampu. Akhir kata, usah dipandang enteng akan perkara ini agar masyarakat sedar akan kewajipan yang ditetapkan ke atas mereka. Dalam masa yang sama supaya masyarakat tidak mengambil mudah dengan meninggalkan puasa atas alasan ditimpa keuzuran tanpa sebarang bukti yang jelas dan meyakinkan.
[1] Hasan bin Ahmad al-Kāff, al-Taqrīrāt al-Sadīdah fī al-Masā’il al-Mufīdah. (Yaman, Ḥaḍramawt: Dār al-Mīrāth al-Nabawī), 456.
[2] Abū Bakr Uthmān Shaṭā. I‘ānat al-Ṭālibīn ‘alā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Mu‘īn. (Dār al-Fikr 1997), 2: 272.
[3] Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muhammad bin Ahmad. Minḥat al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. (Riyad: Maktabah Rushd li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2005). Hadis no. 4505. 7: 532.
[4] Al-Māwardī, Abu al-Hasan Alī bin Muhammad, al-Ḥawi al-Kabīr fī Fiqh al-Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī. (Beirut, Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 3: 466.
[5] Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muhammad bin Abi al-Abbās, Nihāyat al-Muḥtāj ’ilā Sharḥ al-Minhāj. (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 3: 193.
[6] Al-Khaṭīb al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muhammad bin Muhammad, Mughnī al-Muḥtāj ’ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj. (Beirut, Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 2: 174.
[7] Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muhammad bin Abi al-Abbās, Nihāyat al-Muḥtāj ’ilā Sharḥ al-Minhāj. (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 3: 193.
[8] Al-Haytamī, Ibn Ḥajar Ahmad bin Muhammad, Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj. (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), 3: 440.
[9] Ibn Rif‘ah, Najm al-Dīn Ahmad bin Muhammad, Kifāyat al-Nabīh fī Sharḥ al-Tanbīh. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), 6: 239.
[10] Abū Bakr Uthmān bin Muhammad Shaṭā. I‘ānat al-Ṭālibīn ‘alā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Mu‘īn. (Dār al-Fikr, 1998), 2: 271.
[11] Al-Damīrī, Kamāl al-Dīn Muhammad bin Musā, al-Najm al-Wahhāj fī Sharḥ al-Minhāj. (Jedah, Dār al-Minhāj, 2004), 3: 339.
[12] Dr. Labib Najib, Mi’atu Mas’alatin wa Mas’alatun fī al-Ṣiyām wa Mā Yata‘allaqu bih, 31.
[13] Abu Zakariyya, Muḥy al-Dīn bin Sharf al-Nawawī, Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab, (Maktabah al-Irshād 1970), 6: 263.
[14] Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muhammad bin Abu al-Abbās, Nihāyat al-Muḥtāj ’ilā Sharḥ al-Minhāj. (Dār al-Fikr 1984). Jil. 3, ms. 205; Al-Damīrī, Kamāl al-Dīn Muhammad bin Musā, al-Najm al-Wahhāj fī Sharḥ al-Minhāj. (Jedah, Dār al-Minhāj, 2004), 3: 343.